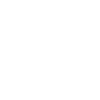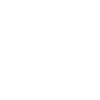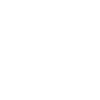Catatan Pengarang
Awalnya, saya benci hal-hal berbau militer. Apapun itu: model rambut, kelakuan, seragam doreng, senapan, granat, tank, dan sebagainya. Menonton filmnya pun ogah! Saat itu, film militer yang paling saya ingat adalah Tour of Duty. Serial itu mempertontonkan pria-pria berambut cepak berpatroli di hutan-hutan Vietnam. Tubuh mereka berkeringat, bersimbah darah, dan belepotan lumpur. Apa menariknya, coba?
Saya benar-benar tidak habis pikir dengan orang yang mengatakan bahwa tentara itu gagah, idaman setiap wanita, atau el macho. Sewaktu mahasiswa, saya tertawa masam begitu tahu teman dekat saya memutuskan bergabung dengan UKM Menwa (Resimen Mahasiswa).
"Mahasiswa demo menyerukan cabut dwi-fungsi ABRI, kamu malah gabung organisasi semimiliter? Salah jalan hidupmu! Apa sih yang mengagumkan dari korps rambut cepak itu? Mereka kan suka menggencet sipil, kasar, arogan, merasa kelasnya lebih tinggi dari kita! Kenapa malah dipuja-puja?" begitu saya biasa memprotesnya.
Ya, demikian antinya saya dulu terhadap militerisme.
Tapi seiring berjalannya waktu, saya berubah pikiran sendiri. Saya mulai membayangkan, betapa kacaunya negara seandainya tidak ada tentara. Bagaimana bila terjadi perang dengan negara lain? Meletus pemberontakan di berbagai daerah? Ada aksi terorisme? Tiba-tiba, muncul monster godzila dari Laut Jawa? Atau terjadi bencana zombie?
Oke, dua yang terakhir itu saya cuma bercanda. Namun bayangkan bila salah satu atau beberapa kondisi tadi benar-benar terjadi. Sementara cadangan pasukan TNI terbatas. Belum lagi, seandainya pemuda-pemuda kita terlanjur membenci militerisme. Dari tahun ke tahun, jumlah calon yang mendaftar di Kodim terus menurun.
Solusinya, pasti segera diberlakukan wajib militer. Yang tidak suka dan tidak mampu pun jadi dipaksa ikut berbaris memegang bedil! Waaaah.... Makanya, akhirnya saya bersyukur melihat di Indonesia masih banyak pemuda yang antusias mendaftar TNI.
Menjadi tentara itu pengabdian luar biasa. Jika ada ancaman atau gangguan terhadap keutuhan bangsa, baik yang remeh maupun yang risikonya nyawa, merekalah yang dimajukan terlebih dahulu. Mereka pun harus berpisah dengan keluarga, pacar atau hobinya, entah untuk sementara atau selamanya. Demi apa, coba? Demi keamanan kita semua sebagai warga negara!
Saya jadi angkat topi untuk korps doreng. Meskipun tetap tidak sampai memuja-muja mereka, setidaknya, opini saya terhadap tentara dan dunia mereka saat ini menjadi positif. Apalagi setelah saya mendengar bahwa pendekatan TNI sekarang sudah (lebih) humanis, bukan lagi mengutamakan kekerasan. Kerenlah kalau memang begitu.
Yang jelas, sebagai penulis yang memfokuskan diri pada genre thriller, saya tahu bahwa menulis tema militer merupakan sebuah tantangan tersendiri. Saya pernah menulis novel berkaitan dengan makhluk supranatural, psikopat, juga alien. Lantas, militer? Kenapa tidak!
Namun, yang selalu muncul di benak adalah, "Nantilah itu! Yah, lima atau 10 tahun lagi saja...."
Sampai datanglah email dari Noura Books. "Brahm, berani nggak nulis novel politik-militer?" singkatnya, begitulah tantangan dari penerbit di bawah payung Mizan Group ini.
Saya termenung beberapa saat. Bukan karena bingung antara menjawab "ya" atau "tidak". Tapi, bingung antara "mampu" atau "tidak". Sebab, meskipun perspektif saya tentang orang-orang militer sudah banyak berubah, tetap saja, saya tidak tahu apa-apa tentang militer.
Walau begitu, akhirnya saya terima tantangan tersebut. Hanya, saya minta waktu agak lama untuk belajar dan menambah wawasan dulu. Apalagi, latar cerita kemudian kami sepakati Papua. Itu usulan dari saya sendiri lho. Hahaha, benar-benar cari sengsara ya! Sudah tahu militer sendiri itu tema yang sulit, masih diperumit pula dengan latar Papua!
Tapi, yah, saya memang merasa harus mencambuk si mental comfort zone dalam diri saya, sekadar supaya tidak banyak menguap bosan ketika menulis. Alhamdulillah, akhirnya jadilah Tiga Sandera Terakhir ini. Semoga Anda berkenan membacanya.
Pesan Novelnya Sekarang